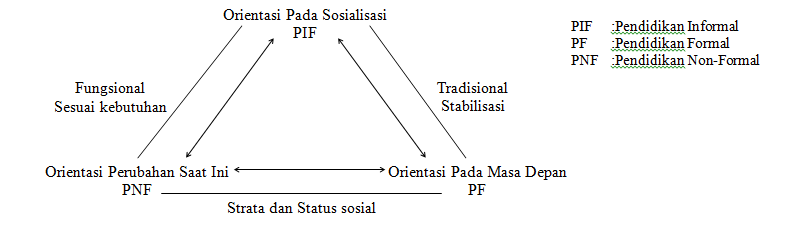Selamat Datang di Blog alumni MKARI 2014.
Surabaya
Kegiatan MKARI di GKIN Air Hidup Surabaya bulan Nopember 2014
 |
| Pembukaan MKARI di GKIN Air Hidup Fasilitator: Agus Santoso, Natalia Nunuhitu, Heri Chin |
 |
| Pembukaan MKARI di GKIN Air Hidup Fasilitator: Agus Santoso, Natalia Nunuhitu, Heri Chin |
 |
| Presentasi tiap kelompok tentang keberagaman |
 |
| Mengenal dan menerima Keberagaman |
 |
| Talk Show bersama Host Televisi di Surabaya, Sdr. Harold Pah. Alumni Universitas Petra Surabaya |
Moral dan Agama Remaja
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu
tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang
diharapkan oleh kelompok dari padanya dan kemudian mau membentuk perilakunya
agar sesuai dengan harapam social tanpa terus dibimbing,diawasi didororng dan
diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak.
Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu berproduksi. Salzman mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.
Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu berproduksi. Salzman mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah,
maka masalah "Perkembangan Moral dan Keagamaan Remaja" dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1.
Bagaimana
perkembangan moral remaja?
2.
Faktor-faktor
apa yang mempengaruhi perkembangan moral remaja?
3.
Bagaimana
pula perkembangan keagamaan remaja?
C. Prosedur Pemecahan Masalah
Pemecahan
masalah yaitu langkah-langkah yang ditempuh dengan pendekatan Metode Library
Research (kepustakaan) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
D. Sistematika pembahasan
Makalah
ini terdiri dari tiga bab, yaitu pertama pendahuluan meliputi latar belakang
masalah, perumusan masalah, proses pemecahan masalah dan sistematika pembahasan
itu sendiri.
BAB II PEMBAHASAN
A. Perkembangan Moral Remaja
Istilah
moral berasal dari kata Latin "mos" (Moris), yang berarti adat
istiadat, kebiasaan, peraturan/niali-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan
moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai
atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu, seperti:
1.
Seruan
untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan,
memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain, dan
2.
Larangan
mencuri, berzina, membunuh, meminum-minumanan keras dan berjudi.
Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Sehingga tugas penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak.
Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya.
Tidak kalah pentingnya, sekarang remaja harus mengendalikan perilakunya sendiri, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Mitchell telah meringkaskan lima perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja yaitu:
a.
Pandangan
moral individu semakin lama semakin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret.
b.
Keyakinan
moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah.
Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominant.
c.
Penilaian
moral menjadi semakin kognitif. Ia mendorong remaja lebih berani menganalisis
kode social dan kode pribadi dari pada masa anak-anak dan berani mengambil
keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya.
d.
Penilaian
moral menjadi kurang egosentris.
e.
Penilaian
moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral
merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan psikologis.
Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang oleh Piaget disebut tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proporsi. Jadi ia dapat memandang masalahnya dari berbagai sisi dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan.
Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral ketiga, moral moralitas pascakonvensional harus dicapai selama masa remaja.tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip dan terdiri dari dua tahap. Dalam tahap pertama individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam tahap kedua individu menyesuaikan dengan standar sosial dan ideal yang di internalisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang-orang lain dan bukan pada keinginan yang bersifat pribadi.
Ada tiga tugas pokok remaja dalam mencapai moralitas remaja dewasa, yaitu:
a.
Mengganti
konsep moral khusus dengan konsep moral umum.
b.
Merumuskan
konsep moral yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode prilaku.
c.
Melakukan
pengendalian terhadap perilaku sendiri.
Perkembangan moral adalah salah satu topik tertua yang menarik minat mereka yang ingin tahu mengenai sifat dasar manusia. Kini kebanyakan orang memiliki pendapat yang kuat mengenai
tingkah laku yang dapat diterima dan
yang tidak dapat di terima, tingkah laku etis dan tidak etis, dan cara-cara
yang harus dilakukan untuk mengajarkan tingkah laku yang dapat diterima dan
etis kepada remaja.
Perkembangan
moral (moral development) berhubungan dengan peraturan-peraturan dan
nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya
dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral (imoral).
Tetapi dalam dirinya terdapat potensi yang siap untuk dikembangkan. Karena itu,
melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain (dengan orang tua, saudara
dan teman sebaya), anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang
boleh dikerjakan dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan.
Teori
Psikoanalisis tentang perkembangan moral menggambarkan perkembangan moral,
teori psikoanalisa dengan pembagian struktur kepribadian manusia menjadi tiga,
yaitu id, ego, dan superego. Id adalah struktur kepribadian yang terdiri atas
aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Ego adalah struktur
kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang
rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Superego adalah struktur
kepribadian yang terdiri atas aspek social yang berisikan system nilai dan
moral, yang benar-benar memperhitungkan "benar" atau
"salahnya" sesuatu.
Hal
penting lain dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah orientasinya untuk
mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan
tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Semakin tinggi tahap
perkembangan moral sesorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap
dan bertanggung jawabdari perbuatan-perbuatannya.
Menjadi Fasilitator 2
Memperhatikan
pokok-pokok pikiran di atas, sepertinya sungguh amat sukarlah untuk mengatakan
dengan segera apa fasilitator itu dalam hubungan dengan tugas dan fungsinya,
walau secara implisit hal tersebut telah tersirat di dalamnya. Barangkali akan
lebih mudah menyebutkan beberapa karakteristik fasilitator yang memberi
gambaran peranannya :
- FASILITATOR itu bukan guru. Ia bukan satu-satunya sumber dan penyalur pengetahuan bagi dan kepada murid, Namun demikian salah satu tugasnya adalah mengajar, dengan cara yang khas, yang harus terus-menerus dipelajarinya.
-
FASILITATOR itu bukan
satu-satunya pemilik pengalaman dan dengan demikian dialah satu-satunya
otoritas dalam proses belajar. Namun demikian pengalamannya dapat menjadi
sumber belajar bagi warga belajar lainnya, sama seperti pengalaman mereka dapat
menjadi sumber belajar bagi fasilitator. Pada saat yang sama, walaupun ia bukan
bukan satu-satunya otoritas dalam proses belajar yang harus digugu dan ditiru,
namun salah satu tugasnya adalah memberi, menyajikan MODEL, yang dapat
diteladani dan ditiru oleh warga belajar.
-
FASILITATOR adalah seorang
process-helper. Ia adalah seorang teknisi proses belajar yang mendorong
terjadinya penemuan (discovery) pada warga belajar. Karenanya ia
haruslah seorang yang cakap dalam berkomunikasi, baik secara pribadi
(inter-personal) maupun dalam kelompok. Ia harus cakap dan trampil menggunakan
berbagai media komunikasi. Ia harus seorang yang articulate, yang dapat
menyampaikan maksudnya dengan kata-kata yang jelas dan tepat. Ia harus cakap
dan trampil pula untuk menyajikan permainan-permainan berbagai model pengalaman
berstruktur, dan menggunakan berbagai mode belajar-mengajar untuk menciptakan
suasana belajar yang mendorong penemuan. Ia juga haruslah seorang pendengar
yang baik dan sekaligus penanya yang baik.
-
FASILITATOR adalah seorang
LEARNER, seorang yang sadar bahwa ia juga sedang belajar dan terus-menerus
belajar.
Untuk
dapat menjalankan peran sebagai fasilitator dengan baik, seseorang perlu
memperhatikan beberapa prinsip fasilitasi yang penting, di antaranya :
MENGAJAR
ADALAH SEKALIGUS PROSES BELAJAR BAGI FASILITATOR ITU SENDIRI.
Dengan
menyadari bahwa pada waktu mengajar, seorang fasilitator adalah sekaligus warga
belajar yang juga sedang belajar dari warga belajar yang lain dan dari proses
belajar itu sendiri, maka ia benar-benar “terlibat” dalam proses belajar itu.
Ia tidak akan kehilangan “learning tension”, suatu kegairahan belajar timbal
balik antara warga belajar dan fasilitator, pada waktu ia belajar “hikmat”
baru, cara baru atau pendekatan baru dalam menerapkan suatu kebenaran dalam
situasi hidup, atau penemuan baru tentang dirinya, kekurangannya, hal-hal baru
yang harus didalaminya lebih lanjut untuk menjadi fasilitator yang lebih
mumpuni, yaitu waktu ada pertanyaan-pertanyaan, tantangan belajar, dsb.,yang
tidak ia temukan jawabannya dalam belajar bersama itu. Semuanya itu dapat
terjadi dalam suatu interaksi dengan warga belajar dan dalam kondisi serta
suasana belajar yang terjadi dan diluar ‘PERKIRAAN” proses belajar yang
direncanakannya. Kalau fasilitator tidak terlibat, dan menghindar dari learning
tension, maka proses fasilitasi yang dikelolanya akan menjadi sajian yang
cemplang, seperti masakan tanpa bumbu.
Prinsip
pertama di atas akan terwujud dalam proses fasilitasi bila fasilitator
memperhatikan prinsip kedua : WARGA BELAJAR ADALAH GURU SAYA. Kalau fasilitator
mengganggap dirinya lebih tahu, lebih menguasai pokok bahasan dari warga
belajar, dan mereka dianggap bodoh, tidak tahu, tidak mampu menguasai pokok
bahasan, dsb., maka yang akan terjadi bukanlah proses fasilitasi. Pengalaman
menunjukkan bahwa orang yang benar-benar ahli dalam suatu bidang pengetahuan,
memperlakukan warga belajar yang dihadapinya dengan rasa hormat, dan menjadikan
mereka cermin bagi proses belajarnya sendiri. Kalau warga belajar kurang
dapat memahami pokok bahasan, tidak diartikannya bahwa mereka bodoh, tetapi itu
menjadi cermin baginya untuk menemukan apa yang harus dipelajarinya lebih
lanjut dalam berkomunikasi. Jadi warga belajar adalah cermin bagi fasilitator
untuk menemukan apa yang harus dipelajarinya lebih lanjut.
Prinsip
yang ketiga adalah : SIAPA SAYA DAN BAGAIMANA SAYA BERTINDAK LEBIH PENTING
DARIPADA APA YANG SAYA KATAKAN/AJARKAN
Fasilitator
yang baik menampilkan MODEL dari tingkah laku dan sikap hidup
yang dikomunikasikannya dan yang dikehendakinya untuk menjadi pengalaman warga
belajarnya. Berbeda dengan peran guru yang harus serba tahu, seorang
fasilitator dapat menjadi model yang baik dengan mengatakan secara jujur, “SAYA
TIDAK TAHU!” Dengan prinsip di atas, maka proses belajar yang baik perlu suatu
kondisi yang sesuai dengan prinsip berikut yaitu : “SAJIKAN SUASANA BELAJAR
YANG MENDUKUNG PENEMUAN (DISCOVERY)! Dengan mengatakan “saya tidak tahu”,
seorang fasilitator menemukan (discover) kebutuhan belajarnya. Dan ini dapat
menjadi pengalaman yang tersaji bagi warga belajar untuk juga menemukan.
Suasana penemuan adalah suatu pemahaman dan pengalaman yang memerlukan
teknik dan metode yang mendorong warga belajar menemukan sendiri apa yang ingin
dipelajarinya dan apa yang ingin diambil sebagai “pelajaran” atau kebenaran
yang akan diterapkan dalam situasinya. (Ingat, fasilitator adalah seorang
teknisi proses, bukan mahaguru yang serba tahu!). Suasana penemuan yang akan
disajikan atau diciptakan oleh fasilitator adalah suasana yang bercirikan :
-
SALING PERCAYA (TRUST) :
Dimana orang dapat mencoba hal-hal baru, mengemukakan pendapat dan ide-ide
baru, kemungkinan-kemungkinan dan jalan keluar tanpa merasa tertekan, takut
atau terancam.
-
PENERIMAAN (ACCEPTANCE) :
Dimana orang “diterima” apa adanya, walau mereka ditantang untuk mencoba kemampuan
dan ketrampilan serta sikap baru, tanpa ada yang merasa takut akan
“dipermalukan”.
-
KEYAKINAN (CONFIDENCE) :
Pada orang-orang yang mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu, bahwa keputusan itu dibuat atas dasar pemahaman dan keyakinan akan
yang benar dan baik serta bermanfaat untuk dirinya maupun lingkungannya. Dan
kalaupun toh tidak, fasilitator tetap confident, bahwa akibat keputusan itupun
akan tetap dapat menjadi learning point atau peristiwa belajar bagi warga
belajar tersebut.
Prinsip
berikutnya adalah : PRAKTEKKAN EXPERIENTIAL TEACHING, yaitu suatu metode
mengkomunikasikan “peristiwa belajar” (learning points) dengan menciptakan
suatu pengalaman bagi warga belajar. Bisa dilakukan dengan suatu simulasi,
penyajian pengalaman berstruktur yang berupa permainan-permainan, role play
dsb. Pengalaman berstruktur itu kemudian diproses mengikuti langkah-langkah
tertentu sehingga warga belajar dapat “menemukan” apa yang ingin
dipelajarinya. Ingat fasilitator bukan guru!
Prinsip
berikut adalah : MENGAJARKAN DENGAN MMPERHATIKAN POLA BELAJAR WARGA BELAJAR.
Setiap orang mempunyai cara dan pola belajar yang berbeda. Para
ahli membedakan pola belajar dengan berbagai cara. Ada Ada Ada
Disamping
hal tsb., tipe kepribadianpun mempengaruhi proses belajar-mengajar. Ada
Diskripsi
tipe kepribadian yang lain yang banyak dikenal adalah introvert dan extrovert,
tipe pemikir dan perasa, atau yang intuitive. Masing-masing dengan ciri
kepribadian, pola tingkah laku dan cara berinteraksi yang berbeda, yang dapat menjadikan
proses belajar penuh dengan ketegangan-ketegangan (tensions) atau suatu
pengalaman yang memperkaya masing-masing warga belajar, tergantung bagaimana
fasilitator membawa dirinya dan menjalankan perannya.
Setelah
memahami beberapa prinsip fasilitasi di atas, seorang fasilitator perlu
mengembangkan sikap-sikap yang mendukung peran dan fungsinya, antara lain :
RENDAH
HATI : Yang terpancar dari sikap dan kesadaran bahwa SAYA TIDAK DAPAT MENGAJAR
ORANG LAIN, karena belajar yang mendalam, yang mempengaruhi sikap hidup dan
tingkah laku adalah suatu PENEMUAN, yang tidak dapat DIAJARKAN, tetapi
diperoleh melalui suatu proses SELF-DISCOVERY. Penemuan-sendiri seperti itu
tidak dapat diajarkan, karena pada waktu diajarkan dampaknya tidak lagi sedalam
dan seefektif penemuan itu sendiri. Karena itu daya tarik menjadi fasilitator
adalah dalam hal menjadi LEARNER, atau warga belajar, bukan guru yang mengajar.
EMPHATI
: Suatu sikap untuk mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sensitif
terhadap apa yang menjadi kekhawatiran orang lain, maupun yang paling dianggap
berharga oleh orang lain. Kesedihan warga belajar adalah kesedihannya sendiri.
Sukacita mereka adalah sukacitanya. Warga belajar sendiri. Kita sendirilah yang
paling tepat memilih dan pilihan itu adalah pilihan yang paling tepat.
Sumber-sumber
dan Acuan :
1.
Srinivasan, Lyra, Perspective on Non-Formal Adult Learning, World Education, 1977
2.
Fordham, Paul, Participation, Learning and Change, Commonwealth Secretariate,
1980
3.
Knowles, Malcolm S., The Modern Practice of Adult Education, Follet Publishing Company,1980.
4.
Kyle, David, World Vision Train the Trainer Workshop, Skopos Corporation, 1984
5.
La Haye, T., Spirit Controlled Temperament
6.
Materi Lokakarya Cross-Cultural Facilitator’s Workshop.
7.
Bina Swadaya, Risalah Lokakarya Media Pendidikan Orang Dewasa, 1981
Menjadi Fasilitator 1
Oleh : Tri Budiardjo
FASILITATOR
adalah sebuah sebutan fungsi dalam proses belajar-mengajar. Kata itu berasal
dari bahasa Latin yang mempunyai pengertian : menjadikan sesuatu dapat berjalan
dengan lancar, mulus, seperti fungsi minyak pelumas pada engsel pintu. Jadi
kata fasilitator mempunyai pengertian dasar : menjadikan mudah, menjadikan
sesuatu berlangsung mulus, atau memperlancar proses.
Kata
FASILITATOR dalam bahasan ini dipakai dalam konteks belajar-mengajar yang
didasarkan pada suatu pendekatan belajar yang khas, yang disebut pendidikan
orang dewasa, pendidikan luar sekolah, atau secara umum, pendidikan non-formal.
Oleh karena itu untuk memahami peran FASILITATOR, perlu dipahami konsep dan
pendidikan non-formal tersebut. Pendidikan non-formal, bukanlah sekedar jenis
pendidikan yang berbeda dari pendidikan formal. Terlalu sempit pula barangkali
kalau pendidikan non-formal ini dilihat sebagai cara baru, metoda
mendidik baru atau bentuk baru mendidik. Pendidikan non-formal ini mempunyai
essensi dan tujuan yang sangat berbeda dengan pendidikan pada umumnya.
Pendekatan terhadap proses belajar-mengajar yang non-formal ini dapat dilihat
sebagai suatu muara yang terjadi dari berbagai arus/aliran sungai-sungai
pikiran dan disiplin yang beraneka ragam. Pendidikan non-formal ini dapat
dikatakan berakar pada suatu proses analisa sosial yang melahirkan
gerakan-gerakan yang memberontak terhadap sekolah. Tetapi pada saat yang sama berhutang
budi pada pendekatan penerapan psikoterapi (yang biasa dilakukan pada
konsultasi individu) pada dunia pendidikan yang dikenal sebagai pendekatan
non-directive teaching. Demikian pula, pendidikan non-formal ini berkembang tak
lepas dari perkembangan ilmu pendidikan. Khususnya yang dikenal sebagai
Andragogy atau pendidikan orang dewasa.
Nama-nama
Ivan Illich dan Paulo Freire akan sangat sering terdengar bila pendidikan
non-formal dibicarakan. Memang mereka berdualah yang memberontak terhadap
sistim sekolah. Keduanya menggugat peranan guru dan sekolah yang terlalu berlebihan.
Ijasah, diploma, gelar dsb, mengkelaskan orang menurut apa yang telah diajarkan
kepada mereka oleh guru - dengan demikian dianggap telah memenuhi syarat,
dianggap sebagai yang berhak untuk menjalankan suatu fungsi kemasyarakatan, berhak
mendapat previlege tertentu, yang tidak boleh dimiliki oleh mereka yang belum
memenuhi syarat-syarat tersebut.
Hal
ini terjadi, menurut Illich, karena asumsi yang keliru bahwa “ada suatu
rahasia” untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Dan kwalitas hidup itu tergantung
pada seberapa banyak rahasia itu dapat dimengerti oleh seseorang, dan bahwa
rahasia itu hanya dapat dinyatakan dan dipelajari secara bertahap-tahap dan
teratur dan yang dapat membuka serta menyatakan rahasia itu adalah sang guru
saja. Guru menjadi agen tunggal dan satu-satunya penyalur rahasia hidup yaitu
pengetahuan. Oleh karena itu Illich menganjurkan suatu pendekatan proses
belajar yang menyungsangkan konsep sekolah, dimana murid adalah yang
memutuskan, dalam hubungannya dengan lingkungannya, untuk memilih apa yang
mau ia pelajari dan dari siapa ia mau belajar. Pusat belajar tidak pada
guru, tetapi pada murid.
Bagi
Freire, pendidikan formal dilihat sebagai sistim bank, dimana guru sebagai bank
informasi yang menstransfer pengetahuan dan informasi yang penting bagi hidup
ke kepala murid. Dengan demikian hubungan guru dan murid adalah hubungan yang
vertikal, antara yang lebih tahu dengan yang tidak tahu apa-apa, antara yang
berbicara dan yang hanya mendengar. Inilah hubungan paternalistis yang dikecamnya.
Pendekatan pendidikan seperti ini tidak menjadikan murid dilengkapi kesadaran
akan (dan dengan demikian mampu menanggapi) realita konkrit dunia mereka. Sekolah
dianggap menjadi instrument yang paling menentukan dalam membentuk dan
mempertahankan budaya “inggih sendiko” dan budaya “diam” masyarakat.
Menurut
Freire, pendidikan seharusnya mampu menolong orang menjadi makin sadar dan
mampu bertanggung jawab bagi dirinya dan dunianya melalui proses refleksi,
aksi-refleksi, dst., yang disebutnya sebagai praksis. Inti belajar ialah suatu
penemuan (discovery) bukan suatu dikte, yang dapat terjadi melalui suatu dialog
horizontal dimana : tak seorangpun mengajar orang lain, tidak ada orang yang
dapat belajar sendiri, dan orang belajar bersama dan bertindak bersama terhadap
realitanya. Dengan demikian sumber belajar bukan pada guru, tetapi guru dan
murid belajar bersama-sama. Keduanya sama-sama bertanggung jawab untuk terjadinya
proses dimana mereka sama-sama bertumbuh. Proses ini dikenal sebagai
conscientizacao (conscientizacion), yang diartikan sebagai upaya untuk
membangkitkan kesadaran diri yang positif dari seseorang dalam hubungannya
dengan lingkungan dan masyarakatnya. Oleh banyak orang itu sering disebut
sebagai proses penyadaran diri, walau istilah itu belum cukup
menggambarkan makna yang terkandung dalam conscientizacao itu.
Istilah
penyadaran diri atau sejenisnya sebenarnya telah banyak dipakai oleh para
psikolog maupun psikoterapis seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Penerapan
pendekatan psikoterapi dalam proses belajar-mengajar ini oleh Carl Rogers
diartikan sebagai tanggung jawab guru untuk mendorong dan menolong menumbuhkan
kapasitas warga belajar untuk memilih dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Guru
harus “beriman”, bahwa dalam kondisi-kondisi yang tepat warga belajar
akan menyataragakan kemampuan dan kapasitas untuk bertumbuh, menguji diri
sendiri secara kritis, mengejar kemahiran dan secara kreatif mengekspresikan
diri. Dalam proses belajar seperti ini guru mempunyai peran ganda, sebagai
warga belajar yang juga sedang belajar dan sekaligus sebagai nara Rogers
Searah
dengan Rogers, Maslow memperkenalkan konsep self actualization, suatu
pengembangan (ekspansi) citra diri yang positif, pengembangan batiniah,
tendensi berbuat baik, makin bertumbuhnya pemahaman dan apresiasi terhadap
sesama, alam semesta dan diri sendiri, makin bertumbuhnya penerimaan diri,
pemanfaatan bakat dan menikmatinya, bertumbuhnya sikap percaya diri dan
kemandirian, dan sebagai hasil kesemuanya itu, bertumbuhnya kemampuan yang
makin besar untuk mengubah dan membentuk lingkungan. Menurutnya, hidup
lebih baik dapat terjadi kalau orang mengenal dirinya sendiri secara baru, baik
secara pribadi maupun sebagai mahluk sosial. Persepsi dan perasaan positif melahirkan
tindakan-tindakan yang positif. Kesadaran diri-baru yang terwujudkan dalam
perilaku yang positif, dibedakan dari perilaku mampu mengatasi masalah (problem
solving behaviour) yang merupakan salah satu aspek belajar. Jereme S. Bruner
memperkenalkan konsep “autonomy of self reward”, suatu “pahala” yang dengan sendirinya
diterima dan dialami oleh warga belajar bila kemauan belajar itu timbul dari
motivasi warga belajar itu sendiri dan bila mereka secara relatif bebas dari
“iming-iming” pahala dari luar (ijasah, sertifikat, status keteladanan dsb.)
maupun bebas dari ketakutan pada “penghakiman” (tidak lulus, tidak memenuhi syarat,
belum bisa, bodoh, dsb). Dengan demikian warga belajar akan cenderung
mengembangkan ketrampilan-ketrampilan dan keyakinan diri untuk mencari
alternatif, pilihan-pilihan jalan keluar bagi permasalahannya. Peranan guru
disini adalah dalam hal penyediaan kondisi sedemikian rupa sehingga
warga belajar akan bertumbuh kemampuannya dalam mengatasi masalahnya.
Tidaklah
lengkap membahas pendidikan non-formal tanpa menyebut Malcolm S. Knowles yang
sering dijuluki sebagai bapak pendidikan orang dewasa (andragogy). Asumsi dasar
andragogy yang dikembangkannya adalah bahwa orang dewasa mempunyai kebutuhan
psikologis yang dalam untuk tidak hanya bertanggung jawab (self directing)
tetapi juga untuk dipandang oleh orang lain sebagai orang yang bertanggung
jawab (self-directing). Oleh karena guru tidak boleh memaksakan keinginan dan
pandangannya pada murid (yang adalah orang dewasa) tetapi memberikan tanggung
jawab belajar pada murid itu sendiri. Keterlibatan diri adalah kunci bagi
proses belajar. Karenanya perlu dikembangkan teknik-teknik belajar dimana warga
belajar yang adalah orang dewasa dapat menilai kebutuhan-kebutuhannya sendiri,
merumuskan tujuan belajarnya sendiri, ambil bagian dalam tanggung jawab
mengadakan “pengalaman belajar” dan mengevaluasi sendiri program-program
belajarnya.
Dalam
proses ini peranan guru adalah sebagai “teknisi profesional” bagi proses
belajar. Dia bukan penyalur informasi dan pengetahuan. Ia adalah
pembimbing proses dan pada saat sama nara
Dibandingkan
dengan pendidikan formal pada umumnya, maka ada 5 hal yang perlu diperhatikan
dalam pendidikan orang dewasa:
1.
PANDANGAN TENTANG DIRI WARGA BELAJAR (SELF-CONCEPT)
Anak-anak (dan murid pada umumnya) melihat dirinya
sebagai dan dalam hubungan tergantung (dependent). Tidak demikian halnya dengan
orang dewasa yang melihat dirinya atau paling tidak ingin dilihat oleh orang
lain sebagai pribadi yang independen, bertanggung jawab dan self-directing. Memperlakukan
mereka sebagai anak seperti menggurui, mengganggap tidak tahu dan tidak punya
pengalaman, tidak hormat, menyalahkan dsb., sangat tidak memungkinkan
terjadinya proses belajar.
2. PENGALAMAN
Seseorang adalah akumulasi pengalamannya. Seorang
dewasa adalah melimpah dengan pengalaman. Dan pengalaman itu adalah sumber
belajarnya. Mengabaikan pengalaman warga belajar sama dengan membatalkan
kemungkinan belajar.
3. KESIAPAN BELAJAR
Dalam pendidikan formal kesiapan belajar ditentukan
dalam kurikulum. Sebelum seorang siap belajar membaca, ia harus mengenal huruf
terlebih dahulu. Tidak demikian dengan kesiapan belajar bagi orang dewasa.
Mereka sendiri yang menentukan apa yang perlu mereka pelajari berdasarkan
persepsi mereka terhadap tuntutan-tuntutan situasinya.
4. PERSPEKTIF WAKTU
Orang dewasa belajar untuk menghadapi situasinya SAAT
ini. Ini yang membedakannya dari perlunya belajar seorang murid. Murid belajar
untuk masa depannya. Yang dipelajarinya diperlukan untuk nanti, bukan sekarang.
Ia belajar untuk TAMAT, dan kemudian masuk ke dunia BERBUAT, yang bukan belajar
lagi. Tetapi hakekat hidup tidaklah demikian. Belajar adalah proses yang tidak
pernah berhenti dalam hidup. “All living is learning”, kata Confucius. Dan ini
benar untuk pendidikan orang dewasa, dimana belajar bukan merupakan PERSIAPAN bagi
MASA DEPAN, tetapi justru hakekat hidup ini adalah BELAJAR.
5. MATERI BELAJAR
Searah dengan perspektif waktu di atas, orang dewasa
belajar untuk memecahkan masalah. Materi belajarnya adalah “problem centered”.
Pendidikan orang dewasa adalah proses penemuan masalah dan penemuan pemecahan
masalah. Orientasinya adalah PENEMUAN.
Demikianlah
berbagai arus pemikiran yang bermuara dalam suatu pendekatan belajar-mengajar yang
dikenal sebagai pendidikan non-formal, dimana masing-masing memberi segi yang
unik yang menjadikan keseluruhannya suatu “mutiara” berharga bagi proses
belajar dan mengajar. Di dalamnya terkandung pemahaman baru tentang hakekat
peranan dan hubungan antara guru dan murid.
Sedemikian
berbedanya konotasi guru dalam pendidikan formal dibandingkan dengan pendidikan
non-formal ini, sehingga istilah FASILITATOR yang dirasa lebih mewakili
peranannya dan sering digunakan. Demikian pula murid, lebih dikenal sebagai
WARGA BELAJAR.
Untuk memberi gambaran yang lebih luas tentang pendidikan non-formal ini dalam keterhubungannya maupun perbedaan dan persamaannya dengan bentuk dan pendekatan pendidikan yang lain, disajikan diagram di bawah ini.